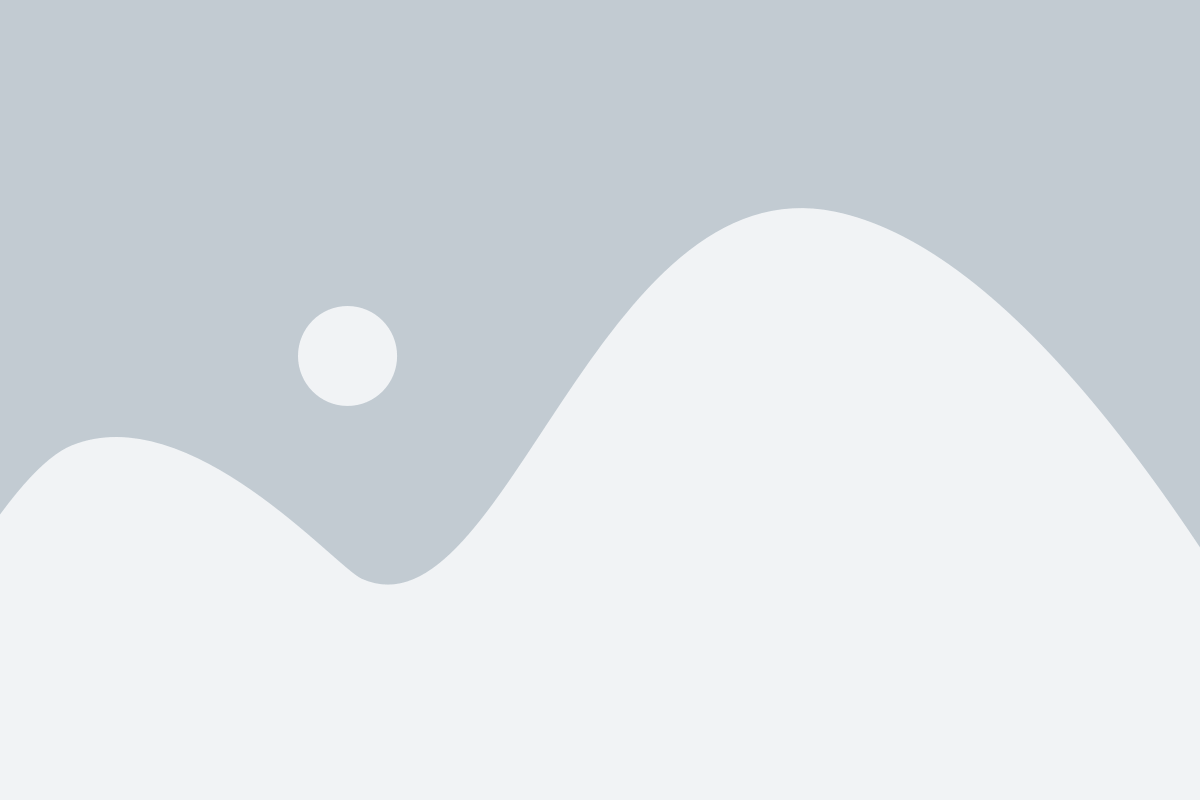Upaya penyelesaian sengketa alternatif (Alternative Dispute Resolution) tidak hanya dikenal dalam kaedah-kaedah hukum perdata, tetapi juga mulai dikenal dan berkembang dalam kaedah hukum pidana. Salah satu jenis ADR yang mulai dikembangkan dalam hukum pidana adalah dalam bentuk mediasi atau dikenal dengan istilah ‘mediasi penal’ (penal mediation).
Di samping istilah tersebut, terdapat juga istilah lain yang dikenal dalam beberapa bahasa di dunia seperti “mediation in criminal cases” atau ”mediation in penal matters” yang dalam istilah Belanda disebut strafbemiddeling, dalam istilah Jerman disebut ”Der Außergerichtliche Tataus-gleich” (disingkat ATA), dan dalam istilah Perancis disebut ”de mediation pénale”.
Semua pengertian atas istilah mediasi yang telah dikemukakan tersebut merujuk pada satu pengertian dalam hukum pidana, yakni mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban untuk menyelesaikan perkara yang tengah dihadapi dengan jalan musyawarah untuk mufakat. Karena sifatnya yang demikian itu, istilah mediasi penal juga dikenal dengan sebutan ”Victim Offender Mediation” (VOM), Täter Opfer Ausgleich (TOA), atau Offender-victim Arrangement (OVA). Kemudian karena sifatnya yang mencari jalan tengah (alternatif) atas suatu penyelesaian perkara pidana, dikenal pula istilah ”the third way” atau ”the third path” dalam upaya ”crime control and the criminal justice system” untuk menyebut mediasi penal ini.
Mediasi penal untuk pertama kali dikenal dalam peristilahan hukum positif di Indonesia sejak keluarnya Surat Kapolri Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) meskipun sifatnya parsial. Pada intinya prinsip-prinsip mediasi penal yang dimaksud dalam Surat Kapolri ini menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR, harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional. Inilah paling tidak pengertian mediasi penal yang dikenal saat ini di Indonesia.
Transplantasi Hukum
Alternatif Dispute Resolution khususnya dalam bentuk mediasi saat ini tengah mengemuka dalam wacana pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal ini diperlukan dalam rangka untuk melakukan perubahan atau juga populer dengan istilah reformasi hukum nasional. Hari Purwadi menyebutkan bahwa reformasi hukum nasional membutuhkan transplantasi hukum, yakni upaya untuk menyesuaikan pembangunan hukum nasional dengan kecenderungan global dan Internasional.
Perubahan dengan cara transplantasi hukum yang dimaksud, agaknya berkesesuaian dengan wacana memasukan mediasi yang biasa dikenal dalam terminologi hukum perdata ke dalam kaedah-kaedah hukum pidana serta dalam rangka memperbaharui kaedah dan sistem peradilan pidana Indonesia yang selama ini tidak mengenal prinsip-prinsip mediasi. Terhadap sistem peradilan pidana sendiri, para ahli diantaranya Mardjono secara tegas membatasi lingkup pengertian sistem peradilan pidana. menurutnya sistem peradilan pidana merupakan sistem pengendalian dan penanggulangan kejahatan. Sistem pengendalian dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan. Sementara penanggulangan dimaksudkan agar kejahatan tetap dalam koridor dan batas-batas toleransi masyarakat.
Senada dengan pengertian yang dikemukakan Mardjono tersebut di atas, OC. Kaligis menambahkan bahwa fungsi utama sistem peradilan pidana adalah untuk melakukan pengendalian kejahatan, yang bertujuan antara lain agar menghindarkan masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan, serta menyelesaikan kasus kejahatan.
Dengan demikian dapat diketahui pula makna dari sistem peradilan pidana ditinjau dari segi tujuannya yaitu untuk menyelesaikan kasus kejahatan. Dari sini terbentuklah beberapa model sistem peradilan pidana, diantaranya Crime Control Model dan Due Procces Model yang pada intinya bertujuan agar penyelesaian kasus kejahatan dapat dilakukan dengan efisiensi dalam penegakan hukum dengan berlandaskan pada prinsip peradilan cepat dan tuntas.
Keadilan
Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep yang diciptakannya yang dikenal dengan “posisi asali” (original position) dan “selubung ketidaktahuan” (veil of ignorance). Melalui teorinya tersebut, Rawls berusaha untuk memosisikan adanya situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat, juga tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya kedudukan, status sosial, tingkat kecerdasan, kemampuan, kekuatan, dan lain sebagainya. Sehingga, orang-orang tersebut dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang.
Teori keadilan yang dikhendaki Rawls ini agaknya seirama dan harmonis dengan konsep hukum progresif yang belakangan diperkenalkan di Indonesia oleh Satjipto Rahardjo. Dengan mengutip pendapat Ellickson, Satjipto Rahardjo menggambarkan bahwa konsep keadilan dan ketertiban dalam kerangka pikir hukum progresif tidak semata-mata bekerja dan diperoleh melalui kerja institusi-institusi kenegaraan. Melainkan sejahteranya keadilan dalam tatanan yang tertib diterima melalui pengakuan hasil bekerjanya institusi bukan negara.
Lebih lanjut Satjipto Rahardjo mengemukakan sebagai berikut,
Asusmi dasar yang ingin diajukan adalah mengenai pandangan tentang hubungan antara hukum dan manusia. Ingin ditegaskan prinsip, “hukum adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Maka setiap kali ada masalah dalam hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki serta bukan manusia yang dipaksa untuk dimasukan ke dalam skema hukum.
Hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. manusialah yang merupakan penentu. … Semakin landasan suatu teori bergeser ke faktor hukum, semakin suatu teori menganggap hukum sebagai sesuatu yang mutlak-otonom dan final. Semakin bergeser ke manusia, semakin teori tersebut ingin memberikan ruang kepada faktor manusia.
Antara teori keadilan yang dibangun Rawls dengan hukum progresif yang diuraikan Satjipto Rahadjo di atas, ada korelasi positif dimana sama-sama bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (rationality), kebebasan (freedom), dan persamaan (equality) guna mengatur struktur dasar masyarakat (basic structure of society). Tatanan yang demikian diproyeksikan akan mampu mencapai tujuan yang terutama dari kaedah-kaedah hukum yakni keadilan yang berdasarkan pada hati nurani manusia.
‘Selubung ketidaktahuan’ yang dimaksudkan oleh Rawls dipandang Satjipto Rahardjo sebagai suatu teori yang bergeser ke faktor hukum, sehingga menganggap hukum dan institusinya sebagai sesuatu yang mutlak-otonom dan final. Kondisi inilah selama ini mengakar dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan di dunia pada umumnya. Yakni ketika korban kejahatan berada dalam kondisi ‘pasrah’ dan hanya menuruti kehendak negara tanpa boleh mengajukan bentuk keadilan yang ingin dirasakannya. Demikian pula dengan pelaku kejahatan, ia harus tunduk dalam bayang-bayang hukuman yang menakutkan, tanpa bisa melakukan negosiasi mengenai bentuk keadilan yang ingin diterimanya.
Hal ini mendapat pembenaran dari Romli Atmasasmita yang menyatakan,
Penderitaan atau kerugian korban diwakilkan kepada jaksa penuntut umum sehingga pada esensinya, perwakilan tersebut dipandang sebagai “mencuri kesempatan” dari konflik antara para pihak dan diwujudkan ke dalam dua pihak, pertama negara dan di lain pihak tersangka pelaku kejahatan.
Pandangan yang demikian itu pada akhirnya melahirkan paham abolisionisme yang dikembangkan oleh Louk Hulsman. Teori yang dikembangkan Hulsman bahkan jauh melampaui kehendak memperbaharui sistem peradilan pidana, yakni menghapus sistem peradilan pidana secara keseluruhannya. Menurutnya sistem peradilan pidana tidak mungkin dapat diperbaharui sebab di dalamnya terkandung cacat struktural. Namun demikian melalui teori abolisionis-nya, Hulsman memandang masih ada satu cara yang dianggap paling realistik yaitu dengan mengubah dasar-dasar struktur sistem peradilan pidana.
Adalah tidak mungkin jika sistem peradilan pidana dihapuskan secara keseluruhannya, kurang tepat pula jika menganggap sistem ini sudah sedemikian kronis hingga tidak mungkin dapat diperbaharui. Tetapi jika merubah dasar-dasar struktur sebagaimana Hulsman di atas, tentu sangat dimungkinkan bahkan di beberapa negara seperti Indonesia, perubahan struktur tersebut pada azasnya justru mengembalikan sistem peradilan pidana kepada sifat asli yang telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia sebagaimana telah penulis uraikan terdahulu.
Alternatif penyelesaian perkara pidana dengan menempuh jalur mediasi penal, dipandang dapat menjadi salah satu pilihan untuk merubah struktur dasar yang dimaksud. Yakni melakukan transplantasi kaedah hukum bahkan lebih jauh mengembalikan dan menata ulang (reformasi) sistem peradilan bangsa Indonesia pada posisi dan sifat-sifat dasarnya.(*)